Globalisasi telah menjadikan dunia yang kita huni ini seperti kampung kecil: semua serba terhubung, dan budaya di suatu tempat yang jauh bisa diadopsi oleh kelompok lain tanpa perlu berinteraksi langsung.
Perubahan masyarakat dunia menunjukkan semakin pudar dan cairnya batas-batas geografis atau ruang. Ada mobilitas social dan intelektual yang semakin intensif; arus orang, barang, informasi, ide dan nilai semakin intensif dan berkelanjutan. Kita menemukan sebuah Islamic Center yang megah di pusat kota London dan Paris, dan pada saat yang sama, kita juga melihat warung-warung KFC, Starbuck, dan parfume Paris di sekeliling kita. Arus pertukaran ini telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam masing-masing kebudayaan. Dunia semakin terintegrasi ke dalam suatu tatanan yang bersifat global, termasuk kebudayaan.
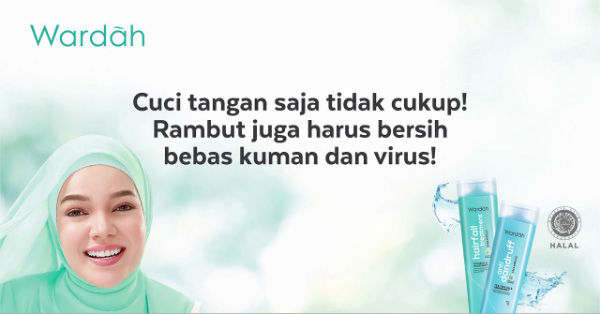 Namun, globalisasi bukanlah ruang bebas dimana semua kita memiliki posisi dan peran yang sama. Di dalamnya ada struktur, dengan peran yang tentu berbeda antara mereka yang berada di center dengan mereka yang berada di pinggiran. Tak bisa dipungkiri bahwa untuk saat ini, pusat struktur itu adalah Barat.
Namun, globalisasi bukanlah ruang bebas dimana semua kita memiliki posisi dan peran yang sama. Di dalamnya ada struktur, dengan peran yang tentu berbeda antara mereka yang berada di center dengan mereka yang berada di pinggiran. Tak bisa dipungkiri bahwa untuk saat ini, pusat struktur itu adalah Barat.
Salah satu wujud globalisasi adalah dunia semakin tergantung dalam komersialisasi dengan budaya konsumtifnya. Komersialisasi membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar yang berakibat pada terjadinya buruh migrant (migratory labour).
Pada saat yang sama, produk-produk teknologi yang dihasilkan juga menyebar sangat cepat ke seluruh dunia. Dunia komersialisasi inilah yang kemudian mengubah wajah dunia, termasuk agama dan kebudayaan.
Bagaimana perubahan itu terjadi? Hal ini diawali dengan perubahan pola produksi yang kemudian mempengaruhi pola konsumsi. Barang-barang terus diproduksi secara massif dengan perubahan teknologi yang sangat cepat. Pada saat yang sama, kebutuhan manusia terhadap barang-barang tersebut relative telah terpenuhi.
Lantas, kemana hasil produksi massif itu akan dipasarkan? Jika pemasaran terhenti, pabrik-pabrik yang menjadi core kapitalisme akan tutup. Untuk keperluan inilah, kemudian diperlukan rekayasa cultural: bagaimana orang-orang yang sudah tercukupi kebutuhannya tersebut mau membeli produk-produk baru yang diproduksi oleh pabrik-pabrik itu. Bujuk agar mereka yang tidak butuh jadi butuh kembali sehingga mau membeli produk baru tersebut.
Pola konsumsi kemudian mengalami pergeseran: dari awalnya untuk memenuhi kebutuhan, kemudian untuk prestige, dan kemudian demi image. Ujung tombak perubahan ini dilakukan oleh media melalui iklan dengan menampilkan figure-figur berpengaruh.
Budaya konsumtif kemudian terbentuk. Sebagai ilustrasi bagaimana kultur ini berkembang, fakta berikut layak dikemukakan. Suatu ketika, di salah satu papan reklame kota London, terpampang gambar seorang perempuan muda berkaos putih. Pada bajunya bagian depan, tertulis jargon menarik: born to shop. Ya, manusia terlahir untuk berbelanja.
Oleh sebab itu, pusat perbelanjaan telah berubah menjadi kiblat baru dalam kehidupan sehari-hari. Belanja jadi hobi, dan wisata kuliner jadi gaya hidup. Dengan kultur shopping ini, kapitalisme bisa beranak pinak di berbagai kawasan di seluruh dunia. Tanpa roh ini, kapitalisme global tak lebih dari sosok seorang manusia yang kurang gizi: lunglai, kulit keriput dan wajah muram. Shopping adalah manifestasi dari kultur konsumtif yang berkembang dalam masyarakat global tanpa melihat agama dan ras.
Ketika penetrasi kapitalisme global semakin intens yang ditandai dengan kemunculan ruang-ruang konsumen, seperti pasar, mal, bank dan lokasi hiburan yang berorientasi pada uang yang sangat mencolok, peran masjid sebagai pusat ibadah juga mengalami tantangan. Ritual harian dan mingguan bukan lagi ke masjid, tapi ke pasar, mal dan pusat rekreasi atau hiburan.
Dalam hal ini, reproduksi kebudayaan di kalangan Muslim tidak hanya dipengaruhi oleh orang tua dan masjid, tapi juga pasar, media dan lingkungan. Dalam banyak hal, saya berpendapat bahwa pasar/pusat komersial lebih berpengaruh daripada keluarga dan masjid. Pasar terus menciptakan kebutuhan baru dan memaksa kita membeli sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok; kita telah menjelma menjadi masyarakat ‘display’ (pamer).
Bagaimana dengan Muslim, apakah terpengaruh oleh kultur konsumtif ini? Karena posisi kita dalam arus komersialisasi adalah konsumen, maka kita selalu melihat ke produsen yang berada di pusat struktur, yaitu Barat. Dalam hal inilah, kita melihat kaum Muslim semakin tersedot ke dalam kultur konsumtif itu.
Sebagai way of life, Islam mengajarkan cara hidup yang sangat kompleks, termasuk dalam cara konsumsi. Ada batas jelas antara kebutuhan dan pemborosan (tabzir). Setiap Muslim dituntut untuk selalu menahan diri dari perbuatan mubazir, sebab seluruh harta yang dimiliki akan dihisab pada hari kiamat: dari mana sumbernya dan bagaimana penggunaannya. Dalam tataran inilah, moral Islam sebenarnya obat mujarab untuk mengobati kecenderungan terjerumus ke dalam kultur konsumtif itu.
Salah satu ritual yang menuntut self restraint yang kuat adalah puasa. Seorang Muslim dituntut untuk mengkonsumsi sekedarnya, dengan jenis makanan yang juga sekedarnya, tidak berlebih-lebihan. Namun, faktanya, puasa yang dilakukan tidak terlepas dari kultur konsumtif itu. Lihatlah tradisi kaum the have Muslim yang ifthar di berbagai restoran dengan menu mahal, dan berbagai acara buka puasa bersama di hotel dan restoran. Tingkat konsumsi yang naik selama Ramadhan seolah berjalan paradox dengan tujuan puasa: untuk menahan diri.
Dalam tataran ini, harus diakui bahwa kaum Muslim sebenarnya juga telah terjebak ke dalam budaya konsumtif itu. Marilah kita jadikan momen puasa ini, apalagi di tengah berjangkitnya wabah Covid-19, untuk kembali kepada pola dasar hidup seorang Muslim yang mengkonsumsi sesuatu atas dasar kebutuhan daripada untuk prestige, image apalagi sekedar untuk display.
Andri Rosadi, Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang







