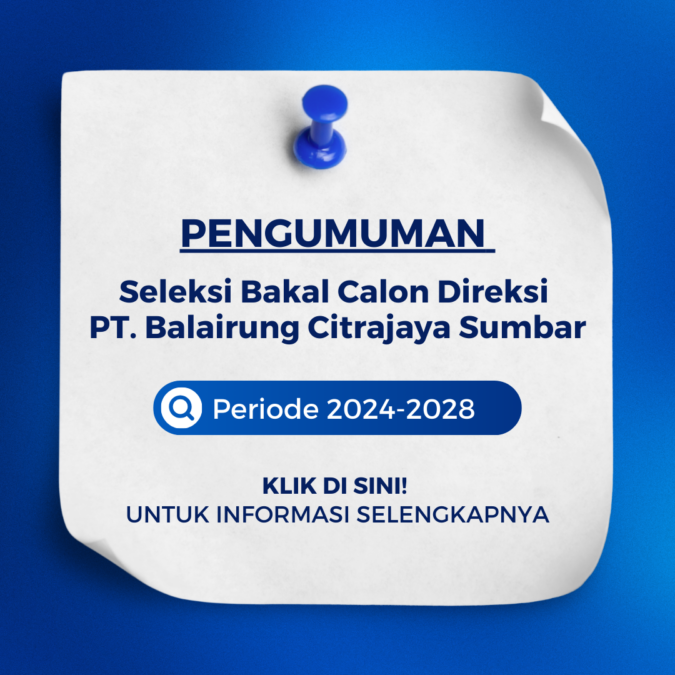Langgam.id - Pada suatu kali di sebuah forum diskusi Facebook tentang khazanah bahasa Minangkabau, saya mengajukan permintaan kepada anggota forum tersebut untuk menyebutkan kosakata carut yang mereka tahu. Saat itu saya ingin meneliti tentang basis sosial yang melahirkan kosakata carut tersebut.
Beberapa anggota forum yang berasal dari daerah yang berbeda di Sumatra Barat menuliskan kosakata yang mereka ketahui. Diskusi di forum itu berjalan lancar hingga kemudian salah satu anggota forum tersebut yang berlaku layaknya dunsanak para raja Minangkabau dari abad-abad lalu mengatakan bahwa semua kata-kata carut tersebut bukan bahasa Minangkabau.
“Kalau bukan bahasa Minangkabau, lalu bahasa mana?” begitu saya bertanya.
Setau saya, dalam bahasa Garundang tak ada kata kalera.
Dalam bahasa Langkitang juga tak ada kata kanciang. Kata karapai tak ada dalam bahasa Siamang. “Pokoknya bukan bahasa Minang,” begitu jawaban yang saya dapatkan, sebuah jawaban yang khas dari orang yang senang berpendapat tapi tidak punya argumen.
Saya mencoba menelusuri argumennya lebih lanjut, hingga kemudian ia mengatakan bahwa kata carut itu bukan bahasa Minang karena bahasa Minang adalah bahasa yang penuh adab, sopan-santun, dan seterusnya.
Seperti anggota forum tersebut, seseorang boleh saja punya ambisi soal keluhuran. Saat ini memang banyak sekali anggota masyarakat kita yang menunjukkan bakat tinggi untuk menjadi polisi moral, terutama bagi yang merasa tidak punya kemampuan lain yang bisa dikembangkan lebih baik.
Tapi, kita tak bisa sewenang-wenang meluputkan kenyataan bahwa kebudayaan tak cuma soal keluhuran, tetapi juga kebanalan. Keduanya sama-sama bagian sah dari suatu kebudayaan.
Minangkabau bukan cuma soal kato nan ampek tapi juga tentang galadia dan makian yang lazim diucapkan orang Minang.
Bagaimanapun juga, semua itu adalah produk dari cara hidup yang kita jalani bersama. Yang luhur dan yang banal itu juga saling berbagi rupa. Kita semakin sulit memberikan garis batas di antara keduanya di tengah semakin jamaknya keluhuran berbulu kebanalan atau kebanalan berbulu keluhuran.
Di titik ini saja kita sudah bisa melihat keterbatasan perspektif moral dalam melihat kenyataan.
Moralitas hanya sanggup membagi dunia ini menjadi baik atau buruk. Kita tentu butuh hidup bersama dengan “kesepakatan” moral tertentu, baik yang diwariskan atau yang kita kembangkan, tapi kita juga harus sadar bahwa kenyataan sehari-hari, yang sama-sama kita geluti bersama ini, tak akan pernah sesederhana “kesepakatan” kita atas moralitas itu sendiri.
Seberapun heroik para pendukungnya, perspektif moral selalu menemui jalan buntu yang tak terelakkan.
Tak ada barang baru di sini. Isu perihal hubungan antara moralitas, bahasa, dan kenyataan sehari-hari sudah menjadi pembicaraan lama dan akan tetap jadi pembicaraan selama kita masih menemukan kasus-kasus serupa, baik di tingkat bahasa daerah ataupun bahasa nasional.
Sebagaimana beberapa waktu belakangan ini, di arena nasional, kita kembali menemukan pelarangan penggunaan kata “anjay” oleh Komnas Perlindungan Anak.
Institusi itu jelas-jelas hanya bermain aman dalam heroisme perspektif moral dan memanfaatkan otoritas institusinya untuk membuat standar moralitas itu sendiri.
Ia tak hanya gagal melihat kompleksitas persoalan, tetapi juga terlalu percaya diri bahwa ia layak menentukan sendiri mana yang baik dan mana yang buruk untuk masyarakat.
Ketika ia sampai di jalan buntu yang diciptakannya sendiri, kita dipaksanya untuk percaya bahwa kita sudah sampai di tujuan.
Kebuntuan perspektif moralitas seperti itu perlu diberi tanda bahaya. Di bawah kuasa moralitas hitam-putih, orang-orang terlalu mudah digoda untuk merasa paling benar.
Di tengah masyarakat kita yang berambisi untuk menjadi paling suci, perangkat moralitas memang sangat mudah untuk mencari kesalahan orang lain atau menjerumuskan orang lain dalam dosa yang seakan-akan tak terampuni.
Mentang-mentang hanya punya palu, bukan berarti semuanya bisa dijadikan paku. Sesuatu yang cuma persoalan personal bisa dilebih-lebihkan jadi persoalan besar yang dianggap bakal merusak bangsa.
Tak heran bila paradigma moralitas yang hitam-putih menjadi senjata paling digemari oleh para cecunguk dalam arena politik atau di arena kebudayaan.
Kita tentu masih ingat, sebagai contoh, di dalam kontestasi politik nasional, cara cepat untuk “membunuh” lawan politik adalah dengan menggunakan isu moral. Kubu-kubu yang saling berlawanan, seberapapun mereka sama-sama menentang serangan moral seperti itu, toh mereka sama-sama sadar dengan kekuataan isu moral dan bahkan tetap memanfaatkannya untuk menyerang lawan.
Dan yang tak kalah bahayanya, penggunaan isu moral adalah cara instan untuk menutupi persoalan yang lebih krusial di dalam kehidupan kita saat ini. Sibuk mengurus moral dengan mengatasnamakan banyak orang adalah cara mengelak yang paling ampuh untuk menghindari tanggungjawab sebenarnya.
Lihatlah para politikus kita telah merasa paling berjasa pada negeri ini hanya dengan mengajarkan ikan cara berenang daripada benar-benar memikirkan bagaimana masyarakat bisa makan tiga kali sehari.
Komnas PA menghabiskan waktunya untuk menunggu pohon pisang berbuah rambutan daripada mengadvokasi persoalan krusial seperti pekerja anak-anak yang semakin banyak dan teraniaya.
Daripada begitu heroik menilai mana yang sah dan mana yang tidak sah sebagai kebudayaan Minang, kita justru lebih butuh mengetahui, misalnya, apa hubungan antara kesenjangan ekonomi di Sumatra Barat dengan semakin banyaknya masyarakat yang bercarut di negeri ABS-SBK ini.
Seseorang menggunakan kata makian bukan karena tidak bermoral sama sekali, tetapi bisa saja karena telah habis kata yang bisa diucapkan untuk menyampaikan rasa putus asa atas kebohongan indah yang tak henti-henti diproduksi massal oleh pemerintah.
Orang-orang yang gemar berjoged di jalan buntu moralitas itu sudah saatnya berhenti menjajakan kotoran kuda berlapis keju. (*/Osh)