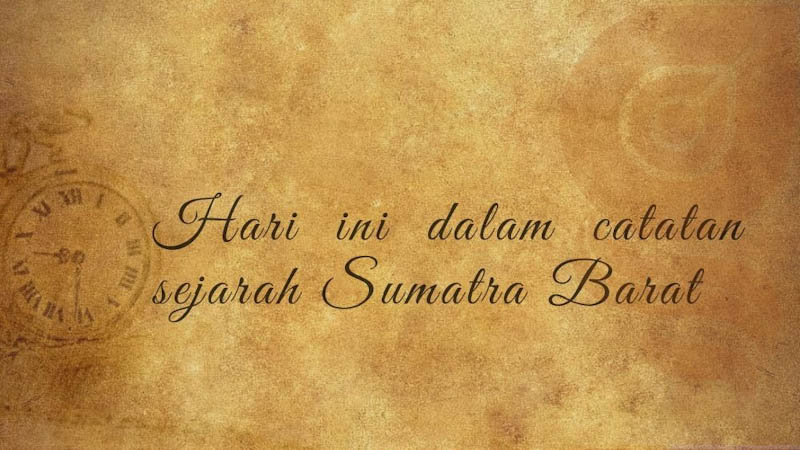Langgam.id – Delapan perempuan menulis petisi untuk Kerapatan Nagari Koto Gadang. Petisi itu terkait aturan adat di nagari yang melahirkan banyak tokoh nasional tersebut. Mereka menyoal larangan perempuan asal Koto Gadang menikah dengan laki-laki dari luar nagari tersebut.
Sebagaimana dikutip dari Azizah Etek dkk dalam Buku “Koto Gadang Masa Kolonial” (2007), petisi itu disebut “Petisi Hadisah: Petisi Perempuan Koto Gadang 6 Mei 1924”. Peristiwa yang terjadi tepat 95 tahun yang lalu dari hari ini, Senin (6/5/2019).
Delapan perempuan tersebut yakni, Hadisah, Rawidah, Sjahroem I, Syahroem II, Roebak, Fatimah, Zabidah dan Roebinah. Mereka menulis petisi sebagai berikut:
“Dengan penuh harapan dan perasaan kami, pertimbangkanlah penghuni
Koto Gadang ingin perubahan.
Adat perkawinan,
telah selalu membatasi kami kaum perempuan semata,
dalam berbagai hal, utama dalam mendapatkan suami
bahagia pada anak perempuan kita tak sempat berjodoh
bahagia kaum laki-laki, bebas
dan kadang ia tidak akan memilih salah satu perempuan kita sendiri.
Akibatnya jika ini terus berlangsung?
Paham betul hukuman yang bakal kami terima
Lihatlah, apa yang terjadi pada Daena muda
menikahi orang Jawa di Medan
bernasib malang dibuang April 1920
Walau menumpuk pujian padanya karena tindakannya
seorang perempuan Koto Gadang sedang dalam posisi berani merentang
waterleiding dari nagari yang lain
kepada kita Nagari Koto Gadang
memungkinkan air nagari yang lain, bisa mengalir
kepada nagari Koto Gadang ini
Hadiah baginya tak lain… hanya pengasingan
Apakah adat ini hanya diberlakukan bagi perempuan saja?
Perempuan berharap… ubahlah pembatasan adat ini…”
Menanggapi petisi tersebut, menurut Azizah dkk, Kerapatan Nagari (lembaga adat di tingkat nagari) menyatakan tentang kebutuhan untuk memelihara nagari yang eksklusif dan menjaga hak milik.
“Tiga puluh enam anggota Kerapatan menolak usul kaum perempuan itu. Yang bersuara lain hanyalah Koedoes Gelar Pamoentjak Soetan, suami Rohana Koedoes,” tulis Azizah, mengutip tulisan Jeffrey Alan Hadler, “The Request of the Women of Koto Gadang”.
Koto Gadang adalah nagari asal Haji Agus Salim, Sutan Sjahrir, Roehana Koedoes serta banyak sekali tokoh. Terletak di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di pinggir Kota Bukittinggi, Koto Gadang sudah terkenal sejak pertengahan abad ke-19, usai Perang Padri.
Nagari ini, menjadi nagari pertama dengan pendidikan paling maju di Minangkabau pada masanya. Sehingga, generasi awal para jaksa, hakim, ahli hukum, dokter dan ambtenaar, umumnya berasal dari nagari ini.
Meski maju secara pendidikan, ada sebuah aturan adat kontroversial yang masih berlaku hingga awal abad ke-20. Aturan adat tersebut, melarang perempuan asal Koto Gadang menikah dengan laki-laki dari luar nagari tersebut. Namun, aturan itu tidak berlaku untuk laki-laki.
Sebagaimana diceritakan dalam Buku “Koto Gadang Masa Kolonial”, ada seorang perempuan asal Koto Gadang bernama Daina yang malanggar aturan tersebut. Daina yang bekerja sebagai asisten pos di Medan menikah dengan teman sekantornya Pomo, asal Jawa.
Daina kemudian dijatuhi sanksi adat ‘buang tingkarang’, tak diakui sebagai orang Koto Gadang karena menikah tidak dengan laki-laki dari Koto Gadang. “Kita terhenyak ketika membaca, bagaimana dapat terjadi peristiwa pembuangan secara adat, seperti yang terjadi pada Daina,” tulis Sosiolog Muchtar Naim dalam pengantar buku tersebut.
Sanksi ini mendapat kritik keras dari orang-orang Koto Gadang sendiri dan menjadi polemik dalam media nagari SKG. Salah seorang perantau asal Koto Gadang B. Salim dalam surat bulan Agustus 1920 mengikritik sanksi tersebut. Reaksi berikutnya datang dari N. Zakir Salim dan D. Salim.
“… memberi hormat kepada Daina tentang keberaniannya dalam melanggar adat yang tidak juga mungkin akan dipertahankan lagi karena menilik keadaan zaman sekarang. Bukannya kami menyalahkan pendapat orang tua-tua. Kami mengaku bahwa adat ini pada masanya boleh jadi sangat berfaedah, tetapi sepanjang pikiran kami untuk zaman sekarang tidaklah dapat dilanjutkan lagi adat itu dengan sekencang-kencangnya…” tulis Zakir dan D. Salim.
Yang mengkritik adalah anak-anak Sutan Mohammad Salim, berhadapan dengan kelompok adat yang dipelopori oleh Amir Sutan Makhudum (AMS) yang kemudian menyandang gelar Penghulu Datuk Narayau.
AMS, menurut Azizah Etek dkk dalam Buku ‘Koto Gadang Masa Kolonial’ (2011), merupakan anggota redaksi SrKG (Soeara Koto Gadang-media nagari). Ia pernah tinggal di Talu, Balai Selasa dan terakhir di Lubuk Begalung, Padang, sebagai mantri polisi.
“Ia paling getol mempersoalkan anak-anak perempuan Koto Gadang yang bersekolah. Ia pula yang mengadukan Rohana Kudus kepada jaksa di Bukittinggi, namun tuduhan itu tak terbukti,” tulis Azizah.
Protes tersebut tak membuat sanksi pada Daina dicabut. Namun, menurut Azizah dkk, kemudian keluarga Daina di kampung bisa kembali berhubungan dengan Daina, seperti menerima kiriman uang, tanpa dipersoalkan lagi.
Pada 1926, Haji Agus Salim menikahkan adiknya dengan sepupunya yang ibunya bukan berasal dari Koto Gadang. Haji Agus Salim sempat dipanggil Land Raad karena itu. Namun, kemudian tak ada yang ‘berani’ mempersoalkannya karena seorang kakak memang berhak menjadi wali nikah adiknya.
Pada 1934, Nurhawaniah, putri Koto Gadang lain, menikah dengan dengan Ahmad dari Pahang, Malaya. “Mamaknya (Pamannya) tidak menyetujui perkawinan itu dan melaporkan kepada ninik mamak Penghulu Nan 24. Namun demikian tidak terdengar hasil apa-apa. Nurhawaniah bernasib baik, tidak seperti Daina,” tulis Azizah.
Sanksi adat itu ternyata melemah. Azizah yang menulis buku bersama Mursyid AM dan Arfan BR mencatat, pada 1935, kemudian keluar aturan adat baru, perempuan Koto Gadang dibolehkan menikah dengan ‘anak pisang’ atau anak dari laki-laki Koto Gadang, meski ibunya bukan orang Koto Gadang. Pada 1952, kemudian dibolehkan dengan orang dari luar Koto Gadang dengan sejumlah syarat.
Setelah itu hingga saat ini, menurut buku tersebut, aturan adat tersebut tidak berlaku lagi. Perkawinan seorang perempuan Koto Gadang dengan orang luar sudah banyak terjadi. “Hal ini sejalan benar dengan isi petisi 6 Mei 1924 yang disampaikan oleh Hadisah bersama tujuh perempuan Koto Gadang,” tulisnya.
Menurut Muchtar Naim, perjuangan emansipasi perempuan dari aturan adat ini patut dicatat dalam khazanah sejarah pergerakan emansipasi perempuan di Indonesia. Termasuk di dalamnya, kepeloporan Rohana Koedoes yang mendirikan organisasi perempuan Kerajinan Amai Setia serta mengelola media perjuangan kaum perempuan Soenting Melajoe. (HM)