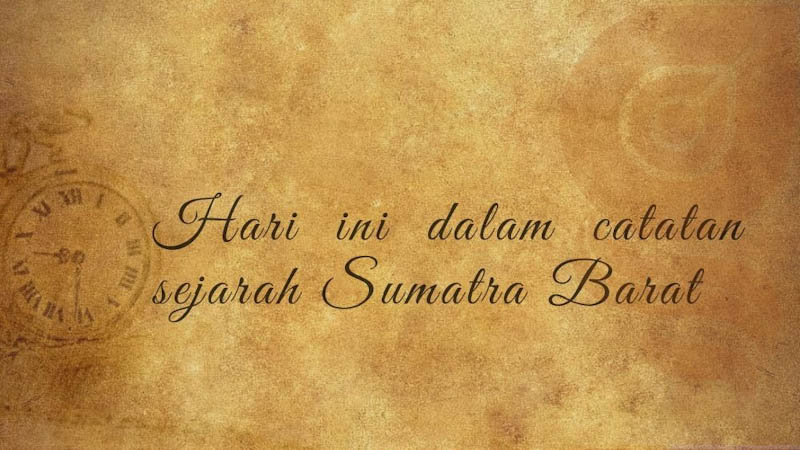Langgam.id – Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan aturan baru terkait pemerintahan di wilayah koloninya. Peraturan yang memberikan otonomi daerah itu, disebut sebagai Decentralisatie Wet.
Aturan ini, diterbitkan Pemerintah Hindia Belanda pada 23 Juli 1903 dalam Staatsblad Nomor 329, atau tepat 116 tahun yang lalu dari hari ini, Selasa (23/7/2019).
Christine ST Kansil dalam Buku ‘Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah 1903-2001’ (2002) menulis, aturan itu mengubah Pasal 68 Regerings Reglement tahun 1854. “Ada penambahan tiga pasal baru (Pasal 68a, 68b, dan 68c) yang memungkinkan untuk berdirinya dewan perwakilan rakyat lokal (locale road).”
Dewan-dewan Perwakilan Lokal tersebut, menurut Kansil, diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga di wilayahnya masing-masing. “Akan tetapi kemudian ternyata desentralisasi yang berdasarkan Decentralisatie Wet 1903 tidak memuaskan,” tulisnya.
Buku ‘Sejarah Kebangkitan Nasional di Sumatera Barat’ (1978) yang diterbitkan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memaparkan penerapan aturan itu.
“Undang-undang ini mengubah sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Di samping itu juga memungkinkan rakyat Indonesia bersidang dan membentuk organisasi-organisasi. Dalam rangka, mengisi dewan-dewan pada lembaga pemerintahan yang diadakan Pemerintahan Hindia Belanda,” tulis buku itu.
Buku itu menyebut, walau perubahan itu dikeluarkan melalui undang-undang, ternyata tidak membawa pembaharuan yang positif terhadap rakyat Indonesia.
Anggota Dewan yang diadakan untuk daerah, selain dari kaula Bangsa Belanda, harus pula pegawai-pegawai yang bekerja pada pemerintahan Belanda.
“Sedangkan pemilihan anggota Dewan terbatas pula. Dengan demikian, anggota-anggota Dewan adalah orang Belanda sendiri, artinya bekerja untuk kepentingan Belanda.”
Buku ‘Sejarah Kebangkitan Nasional di Sumatera Barat’ juga menyebut, sama halnya dengan wilayah lain, di Sumatra Barat, aturan tentang desentralisasi itu tidak membawa perubahan.
Sumatra Barat yang berbentuk keresidenan dipimpin seorang residen. Keresidenan pada masa itu dibagi dalam beberapa Afdeling yang dikepalai seorang asisten residen. Afdeling dibagi lagi ke dalam Onder Afdeling yang dipipin seorang Controleur. Baik residen, para asisten residen dan controleur seluruhnya dipegang orang Belanda. “Tak satupun dari jabatan itu yang dipegang orang Minangkabau.”
Di bawah Onder Afdeling ada tingkat kelarasan, dan di bawahnya terbagi lagi atas nagari-nagari. Pada jabatan inilah orang Minang dibolehkan memimpin.
Sebenarnya, Pemerintah Hindia Belanda pernah melibatkan para tokoh urang awak dalam pemerintahan. (Baca: Bubarnya Keregenan Padang, Akhir Cerita Urang Awak dalam Pemerintahan Kolonial)
Sejarawan Universitas Andalas Gusti Asnan dalam Buku ‘Pemerintahan Sumatera Barat, Dari VOC Hingga Reformasi’ (2006) menulis, pelibatan pribumi dalam pemerintahan, dimulai pada 1823.
“Kesempatan itu muncul seiring keluarnya Provisioneel Reglement tertanggal 4 November 1823. Antara lain memutuskan pembentukan dua daerah administratif setingkat Hoofafdeeling (Afdeeling Utama) untuk masyarakat Bumiputera,” tulis Gusti.
Dua hoofafdeelingen tersebut adalah Padang dan Minangkabau. Keduanya, masing-masing dipimpin seorang pribumi dengan jabatan yang disebut Hoofdregen alias Regen Gadang.
Hal ini menandakan, Pemerintah Hindia Belanda di Sumatra’s Westkust (Sumatra Barat), membuat dualisme pemerintahan.
Selain pemerintahan pribumi tersebut, pada tahun yang sama wilayah Sumatra’s Westkust juga dibagi ke dalam dua pemerintahan kolonial yang dipimpin orang Belanda. Awalnya, dengan wilayah persis sama dengan pemerintahan pribumi, yakni wilayah Padang beserta seluruh wilayah pesisir Sumbar dan Minangkabau yang melingkupi wilayah pedalaman Sumbar.
Bila untuk pemimpin orang Belanda, pimpinan wilayah disebut Asisten Residen atau Controleur, untuk orang Minangkabau, dua pimpinan wilayah tersebut disebut regen gadang.
“Pemberian ruang gerak yang lebih banyak kepada orang Sumatra Barat, karena Belanda membutuhkan dukungan pemimpin lokal,” tulis Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas itu.
Dualisme pemerintahan Belanda di Sumatra Barat berjalan selama puluhan tahun dan berkembang tanpa arah yang jelas sesuai kepentingan Pemerintah Kolonial. Di samping Afdeeling yang paling banyak sampai sembilan, di wilayah Sumbar, pernah ada 17 keregenan.
Namun, justru setelah aturan tentang desentralisasi diterbitkan, keregenan makin dihabisi. Dua keregenan terakhir Padang dan Indrapura dibubarkan Pemerintah Hindia Belanda pada 1910 dan 1911. Praktis setelah itu, tak ada lagi keregenan di Sumbar.
Aturan tentang desentralisasi itu makin terlihat sekedar janji ‘angin surga’, karena lembaga perwakilan rakyat di Sumatra Barat, tak kunjung ada sejak 1903 hingga 35 tahun kemudian.
“Baru pada 1938, Belanda mendirikan Dewan Minangkabau (Minangkabau Raad), yang diketuai langsung oleh residen dan Roesad Dt. Parpatih Baringek sebagai sekretaris,” tulis Audrey Kahin, dalam ‘Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998’ (2003).
Audrey menulis, dewan ini beranggotakan 45 orang, 38 di antaranya orang Indonesia yang dipilih di bawah kontrol ketat pemerintah. “Pemerintah sangat membatasi isu-isu yang boleh dibicarakan di dewan ini,” tulisnya.
Dewan ‘Angin Surga’ di penghujung kekuasaan kolonial ini, berakhir empat tahun kemudian, ketika Pemerintah Hindia Belanda melarikan diri dari Balatentara Jepang yang masuk menguasai Sumbar. (HM)